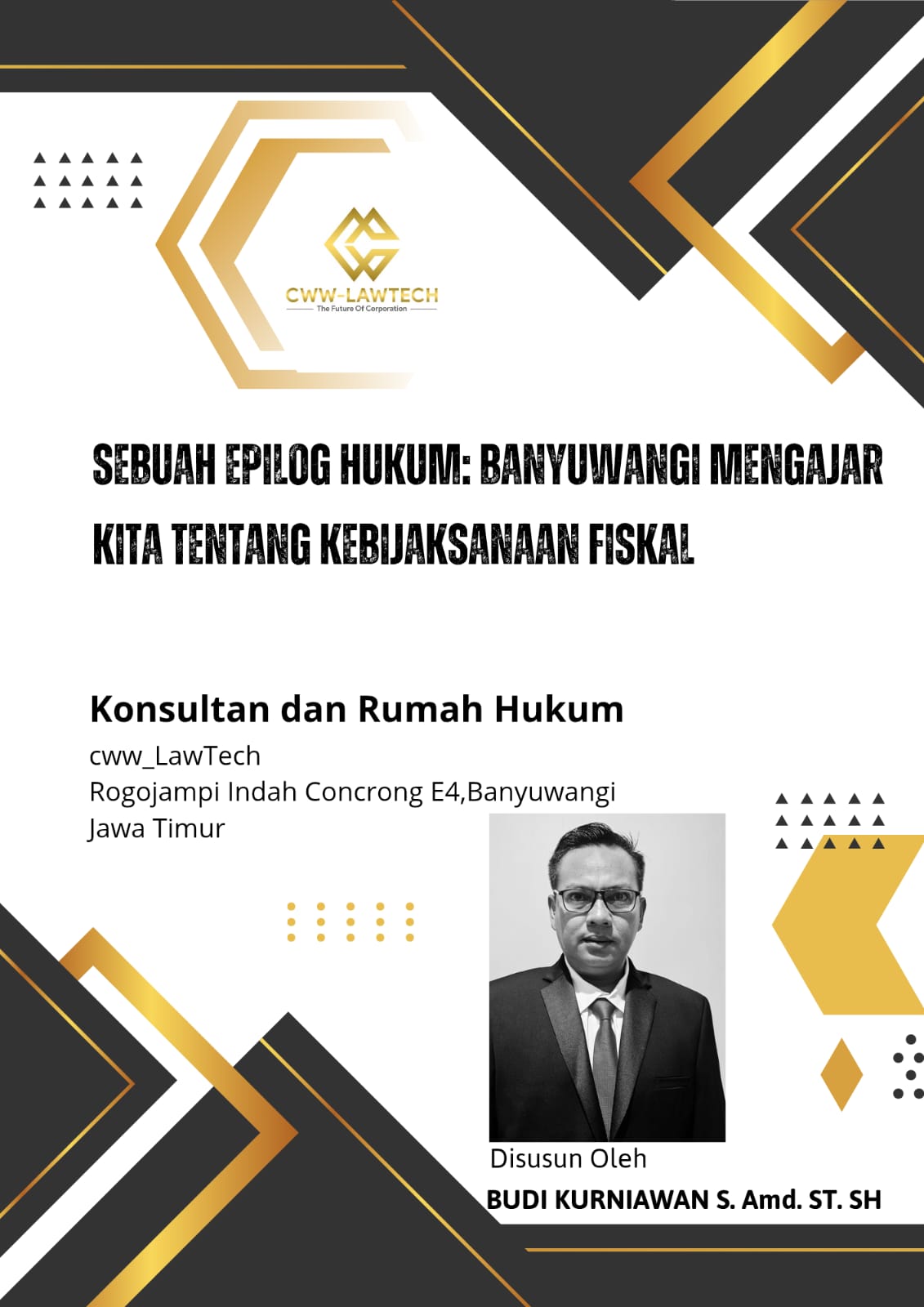
Oleh: Budi Kurniawan Sumarsono, A.Md. ST. SH. (Founder CWW Lawtech)
I. Prolegomena: Hukum Sebagai Dialektika Tanpa Henti
Dalam lanskap ketatanegaraan modern, hukum sering kali dipahami sebagai serangkaian pasal, ayat, dan norma yang kaku, sebuah teks mati yang membatasi gerak-gerik masyarakat. Namun, pandangan formalistik semacam itu sejatinya mengkhianati esensi dari hukum itu sendiri. Hukum adalah sebuah entitas yang hidup, sebuah dialektika yang tak henti antara norma-norma yang tertulis (ius scriptum) dan nilai-nilai keadilan yang bersemayam dalam sanubari rakyat (ius non scriptum). Inilah inti dari doktrin Rechtsstaat, sebuah negara hukum di mana kekuasaan tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan di bawah kendali supremasi hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
Kasus polemik pajak PBB-P2 di Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah episode krusial yang secara gamblang mempertontonkan dialektika tersebut. Apa yang bermula dari sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perubahan tarif, dengan cepat bertransformasi menjadi sebuah diskursus publik yang mendalam, menguji sejauh mana sebuah kebijakan fiskal bisa disebut adil, transparan, dan akuntabel. Peristiwa ini bukan hanya tentang angka-angka dan persentase, tetapi tentang pencarian harmoni antara kepentingan negara dalam mengumpulkan pendapatan dan hak-hak dasar rakyat untuk tidak dibebani secara tidak proporsional.
Opini ini akan membedah secara komprehensif seluruh narasi yang terjadi, dari awal pengusulan Raperda, argumen-argumen yang dimunculkan oleh pihak pemerintah daerah, hingga epilog yang manis di mana nurani eksekutif dan legislasi akhirnya mengindahkan jeritan aspirasi publik. Kami akan menggunakan lensa hukum tata negara, diperkaya dengan diksi-diksi modern dan kearifan filosofis yang mengakar pada tradisi hukum kontinental, khususnya dari Belanda, untuk memberikan sebuah pandangan yang lebih utuh dan mencerahkan.
II. Arsitektur Hukum Pajak Daerah: Sebuah Hierarki yang Sakral
Untuk memahami secara tuntas polemik ini, kita harus terlebih dahulu mengapresiasi arsitektur hukum yang menopang sistem pajak daerah di Indonesia. Sistem ini menganut prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, sebuah asas fundamental yang dikenal dengan adagium lex superior derogat legi inferiori, yang berarti “peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.” .
Pada puncak hierarki ini berdiri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-Undang ini adalah masterpiece legislasi yang memberikan koridor normatif bagi daerah untuk memungut pajak dan retribusi. UU HKPD secara tegas memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis, subjek, objek, dan tarif pajak, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda).
Perda, dalam konteks ini, adalah produk hukum yang sakral. Ia menjadi “kitab undang-undang” bagi daerah, menetapkan norma-norma pokok yang bersifat mengikat bagi seluruh warga dan pejabat. Sebagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang di wilayahnya, Perda hanya dapat dibuat oleh eksekutif (Kepala Daerah) dan legislatif (DPRD) secara bersama-sama, melalui proses yang transparan dan akuntabel.
Di bawah Perda, terdapat Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota (Perwali). Perbup bukanlah peraturan yang berdiri sendiri; ia adalah peraturan pelaksana, atau dalam bahasa hukum, sebuah uitvoeringsbesluit—sebuah keputusan yang bertujuan untuk melaksanakan perintah-perintah yang termaktub dalam Perda. Perbup tidak boleh dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah, menyimpangi, atau bahkan bertentangan dengan Perda. Prinsip ini sangatlah absolut, dan setiap pelanggarannya akan membuat Perbup tersebut batal demi hukum (nietig van rechtswege).
Polemik di Banyuwangi, pada titik awalnya, adalah sebuah cerminan dari kegagalan memahami arsitektur suci ini. Argumentasi awal yang menyatakan bahwa Perda bisa menetapkan tarif tunggal, sementara Perbup akan mengatur klasterisasi multi-tarif, adalah sebuah narasi yang membingungkan dan melanggar prinsip hierarki. Mengapa? Karena Perbup tidak dapat menciptakan norma yang substansinya bertentangan dengan Perda. Itu adalah sebuah misbruik van recht—penyalahgunaan hak atau wewenang.
III. Dilema Fiskal dan Premis yang Keliru: Sebuah Devaluasi Kebenaran
Argumen yang dilontarkan oleh Pemkab Banyuwangi pada awalnya terdengar seperti sebuah solusi yang canggih dan fleksibel. Mereka berdalih bahwa Perda baru, dengan tarif tunggal 0,3%, akan tetap adil karena nantinya Perbup akan memberikan “stimulus” atau klasterisasi yang membuat pajak terutang sama dengan tahun sebelumnya. Namun, sebagai seorang pembelajar hukum keuangan negara, saya melihat ini bukan sebagai solusi, melainkan sebagai sebuah premis yang keliru dan berpotensi menjadi kebohongan publik.
Mari kita bedah secara finansial dan hukum.
Pada dasarnya, ada dua sistem yang dipertentangkan:
* Sistem Lama (Perda No. 1/2024): Menerapkan tarif progresif (multi-tarif), di mana NJOP di bawah Rp1 miliar dikenakan tarif 0,1%, di atas itu 0,2%, dan seterusnya.
* Sistem Baru (Raperda): Menerapkan tarif tunggal (single tarif) 0,3% untuk semua kategori NJOP, dengan janji stimulus di Perbup.
Secara matematis, Perda baru secara fundamental telah menaikkan potensi penerimaan pajak dari objek pajak yang sebelumnya dikenakan tarif 0,1% dan 0,2%. Contoh perhitungan yang saya sampaikan sebelumnya membuktikan hal ini. Pajak yang tadinya Rp 3 juta, tiba-tiba menjadi Rp 4,5 juta. Pemerintah kemudian “berbaik hati” mengembalikan selisihnya melalui mekanisme stimulus yang diatur dalam Perbup.
Ini adalah sebuah devaluasi kebenaran. Pemerintah seolah-olah mengatakan, “Kami sudah menaikkan tarif, tapi jangan khawatir, kami akan mengembalikannya melalui mekanisme lain.” Padahal, stimulus itu sendiri adalah kebijakan yang rapuh, bersifat kondisional, dan bisa dicabut sewaktu-waktu. Wajib pajak tidak memiliki kepastian hukum bahwa stimulus itu akan terus berlaku di tahun-tahun mendatang. Di sinilah letak jurang antara kepastian hukum (rechtszekerheid) yang diatur oleh Perda dan ketidakpastian kebijakan yang diatur oleh Perbup.
Klaim bahwa “nilai pajak yang dibayarkan akan sama” adalah sebuah janji yang didasarkan pada asumsi yang sangat tidak realistis. Asumsi ini mengabaikan dinamika perekonomian dan potensi perubahan kebijakan di masa depan. Dalam dunia keuangan negara yang ideal, pemerintah tidak boleh membangun fondasi fiskal yang rapuh di atas janji-janji yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mutlak. .
IV. Anomali Stimulus dan Peluang Manipulasi: Menyingkap Lapisan Keberadaan
Konsep stimulus atau insentif fiskal bukanlah hal yang haram dalam ilmu keuangan negara. Pemberiannya sah secara hukum, tetapi hanya jika didasarkan pada alasan yang kuat dan transparan, seperti:
* Keadaan Darurat: Di masa pandemi COVID-19, banyak pemerintah daerah memberikan stimulus untuk meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha.
* Mendorong Investasi: Stimulus dapat diberikan kepada sektor industri tertentu untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Namun, menggunakan stimulus sebagai alat untuk menyembunyikan kenaikan pajak adalah sebuah anomali. Ini adalah bentuk maladministratie (maladministrasi) di mana pemerintah menggunakan instrumen yang tidak tepat untuk tujuan yang salah. Alih-alih melakukan perubahan Perda secara transparan dan berdialog dengan publik, pemerintah memilih jalan pintas yang berpotensi melanggar asas transparansi (transparantiebeginsel) dan asas akuntabilitas (accountabilitybeginsel).
Pelanggaran ini membuka pintu lebar bagi peluang manipulatif.
* Ketidakadilan yang Terselubung: Perbup dapat menetapkan kriteria stimulus yang subyektif, membuka celah untuk perlakuan istimewa bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
* Kerentanan terhadap Gugatan Hukum: Wajib pajak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika hakim melihat adanya penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau pelanggaran asas hierarki, Perbup tersebut dapat dibatalkan, dan penagihan pajak harus dikembalikan.
Lebih jauh, penyalahgunaan stimulus juga berpotensi dijerat oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Jika terbukti pemberian stimulus dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan pejabat dan menyebabkan kerugian keuangan daerah, maka unsur pidana korupsi telah terpenuhi. Ini adalah sebuah pengingat bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mengawasi (controleert).
V. Kedaulatan Rakyat dan Jalan Rekonsiliasi: Kembalinya Akal Sehat Politik
Klimaks dari polemik ini adalah sebuah momen yang membahagiakan, di mana akal sehat politik dan nurani legislasi akhirnya berbicara. Keputusan DPRD Banyuwangi untuk mencabut perubahan Raperda dan kembali ke ketentuan lama adalah sebuah kemenangan bagi kedaulatan rakyat (volkssoevereiniteit). Itu adalah sebuah pengakuan bahwa aspirasi masyarakat bukanlah bisikan angin yang dapat diabaikan, melainkan sebuah kekuatan konstitusional yang harus didengar dan diakomodasi.
Tindakan ini juga merupakan sebuah bentuk rekonsiliasi hukum. Pemerintah dan legislatif di Banyuwangi telah memilih jalan yang benar dan berintegritas. Mereka mengesampingkan ego politik dan kembali pada rel hukum yang benar, yakni dengan menetapkan norma yang berkeadilan di tingkat Perda, bukan di tingkat peraturan pelaksana yang lemah.
Peristiwa ini juga mengafirmasi asas proporsionalitas (proportionaliteitsbeginsel)—bahwa setiap kebijakan harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai (peningkatan pendapatan) dan beban yang dikenakan kepada rakyat. Kenaikan pajak yang terlampau tinggi, meskipun legal, dapat menjadi tidak proporsional jika tidak diimbangi dengan perbaikan layanan publik atau jika kondisi ekonomi masyarakat tidak memungkinkan.
VI. Epilog: Sebuah Model Tata Kelola Fiskal Modern
Kasus Banyuwangi memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa hukum bukanlah sebuah alat yang kaku untuk memaksakan kehendak, tetapi sebuah instrumen yang dinamis untuk mencapai harmoni. Ia mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang responsive terhadap dinamika sosial dan ekonomi, dan kepastian hukum (rechtszekerheid) sesungguhnya dicapai ketika hukum mencerminkan keadilan di hati rakyat.
Banyuwangi telah membuktikan bahwa komunikasi yang intensif, keterbukaan informasi, dan kemauan untuk mendengarkan aspirasi rakyat adalah fondasi dari tata kelola fiskal yang modern dan akuntabel. Dengan mengembalikan tarif pajak PBB-P2 ke norma yang lama, mereka tidak hanya mengakhiri sebuah polemik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik yang sempat tergerus.
Ini adalah sebuah langkah maju yang signifikan dalam membangun sebuah negara hukum yang sejati, di mana pemerintah dan rakyat tidak lagi menjadi entitas yang terpisah, melainkan mitra yang bergerak bersama menuju cita-cita bersama: kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua. Dan dalam konteks ini, Banyuwangi telah menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi daerah-daerah lain di Nusantara. (cww)




















